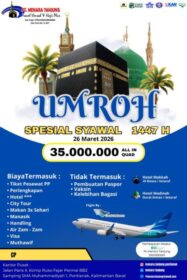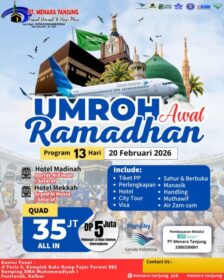FOTO : Bens Jono Hartono
Oleh : Bens Jono Hartono [ Praktisi Media Massa di Jakarta ]
*Pembukaan*
SETIAP kali Gibran Rakabuming Raka tampil di depan publik, entah dalam forum resmi, pertemuan kenegaraan, atau bahkan sekadar meninjau kegiatan rakyat, gelombang komentar sinis, meme sarkastik, hingga olok-olok di media sosial seolah menjadi ritual yang tak pernah absen.
Fenomena ini bukan sekadar masalah personal terhadap Gibran, melainkan potret sosial yang lebih dalam, krisis kedewasaan publik dalam memahami dinamika politik dan regenerasi kepemimpinan di Indonesia.
*Anak Mantan Presiden, Bukan Lagi Anak Kecil*
Gibran menjadi simbol paradoks. Di satu sisi, ia adalah anak mantan presiden, status yang otomatis menimbulkan kecurigaan publik terhadap privilege dan nepotisme politik.
Di sisi lain, ia adalah representasi generasi baru yang menembus politik konvensional dengan gaya teknokratik dan pendekatan pragmatis.
Namun di ruang publik, label “anak Jokowi” selalu menenggelamkan kapabilitasnya. Tak peduli seberapa banyak program sosial atau inisiatifnya yang berdampak, narasi yang lebih kuat tetap, “ia naik karena bapaknya.”
Dalam masyarakat yang trauma oleh oligarki dan dinasti politik, setiap langkah Gibran selalu dibaca sebagai konspirasi kuasa, bukan kontribusi kerja.
*Medsos Arena Politik Emosi*
Di era algoritma dan echo chamber, politik bukan lagi pertarungan ide, tapi pertarungan persepsi. Gibran menjadi sasaran empuk karena ia, muda, viral, dan terkait langsung dengan figur kuat bernama Jokowi.
Setiap ekspresinya, entah diam, senyum, atau salah ucap, langsung dipotong, diedit, dan dijadikan bahan konten satir. Bukan karena kesalahannya fatal, tapi karena keterpaparannya total.
Ironisnya, sebagian besar pembully bukan ingin menegur, tapi mencari validasi identitas melalui penghinaan kolektif. Di situ politik berubah menjadi drama digital, di mana Gibran hanyalah aktor dalam skenario kebencian algoritmik.
*Kegagapan Politik Generasi Lama*
Sebagian elite politik dan aktivis lama juga tak nyaman dengan kehadiran Gibran. Mereka menganggap kecepatan kariernya sebagai ancaman terhadap “pakem perjuangan.” Padahal zaman telah berubah, politik tak lagi digerakkan oleh orasi jalanan, melainkan strategi komunikasi, efisiensi birokrasi, dan konektivitas sosial.
Namun ketidaksiapan generasi lama menerima regenerasi membuat Gibran kerap menjadi sasaran ejekan, bukan karena kinerjanya, tapi karena ia mewakili masa depan yang belum mereka pahami.
*Publik yang Mudah Menghakimi, tapi Enggan Menilai Kinerja*
Ketika Gibran berpidato dengan gaya khas Solo-nya yang singkat dan praktis, publik menyebutnya kurang intelektual. Tapi ketika ia menyampaikan paparan teknokratis, publik menuduhnya sok pintar.
Apa pun yang ia lakukan, selalu salah di mata mereka yang sudah terlanjur memelihara prasangka. Padahal dalam pemerintahan, posisi wakil presiden bukanlah panggung utama, melainkan fungsi koordinatif dan pendamping strategis.
Namun publik yang haus hiburan politik sering menginginkan Wapres tampil seperti influencer, bukan negarawan.
*Bullying sebagai Cermin Ketakutan Kolektif*
Pada akhirnya, bullying terhadap Gibran bukan sekadar masalah individu, tapi refleksi ketakutan kolektif bangsa terhadap perubahan generasi. Ketika anak muda memasuki arena kekuasaan, sebagian masyarakat merasa kehilangan kontrol atas narasi “senioritas.”
Gibran menjadi punching bag dari transisi zaman, antara generasi analog yang belum ikhlas melepaskan kuasa dan generasi digital yang berani mengambil alihnya.
*Penutup*
*Antara Kritik dan Kebencian*
Kritik diperlukan, tetapi bullying adalah bentuk kemalasan berpikir. Kritik membangun sistem, sedangkan bullying hanya menumbuhkan kebencian tanpa arah.
Mungkin sudah saatnya publik Indonesia belajar membedakan antara “mengawasi pemimpin” dan “menghina pemimpin.” Karena di tengah dinamika politik yang keras, bangsa ini butuh kesantunan berpikir, bukan hanya keberanian berteriak.